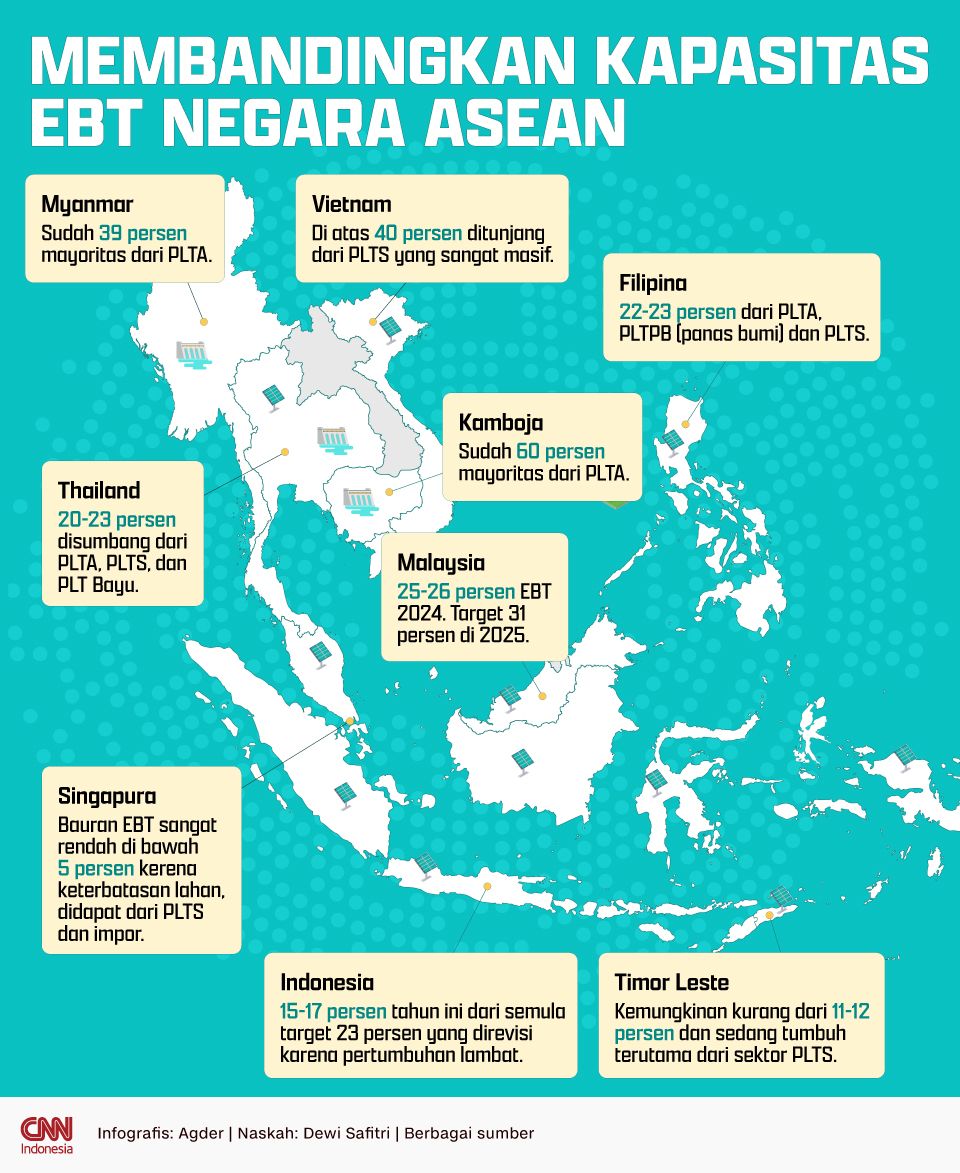Jalan Lamban Transisi Energi RI, Antara Ambisi dan Realisasi

Presiden Prabowo Subianto jelas punya perhatian besar terhadap transisi energi di Indonesia. Setidaknya dalam beberapa pernyataannya di depan publik.
Sejak dilantik Oktober tahun lalu, isu transisi tidak pernah absen dari perhatiannya tiap tampil, baik di forum penting dalam negeri maupun panggung internasional.
Bulan lalu di KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Prabowo menegaska target 100% energi terbarukan Indonesia mulanya dipatok pada 2040. Namun ia mengklaim para ahli pemerintah meyakini target itu bisa dicapai jauh lebih cepat, yaitu dalam satu dekade ke depan, sekitar tahun 2034-2035.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target ini diulang lagi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2006, Jumat (15/08) lalu. Indonesia menurut Prabowo harus "menjadi pelopor energi bersih dunia" dengan capaian target yang jauh lebih cepat yakni tahun 2035.
Namun sebenarnya meski sudah disebut-sebut Prabowo di banyak forum, target-target ini belum disebut dalam dokumen energi dan kelistrikan nasional.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, belum pernah menyebut kapan persisnya akan mencapai transisi energi sepenuhnya, di mana semua jenis energi fosil digantikan oleh energi terbarukan.
Target terbaru dan saat ini masih menjadi pegangan kebijakan adalah Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dirilis Mei lalu, berlaku sampai dengan 2034.
Dokumen ini diumumkan dan disahkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025. RUPTL ini menjadi peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan dan menjadi acuan investasi di sektor ketenagalistrikan.
RUPTL 2025-2034 tersebut menargetkan 76% dari total kapasitas pembangkit listrik sampai tahun 2034 berasal dari energi terbarukan. Sumbernya adalah PLTA, PLTS, panas bumi, bioenergi dan pembangkit nuklir.
Dengan melihat lambatnya pertumbuhan produksi EBT saat ini, berbagai kalangan mengingatkan target RUPTL yang hanya 76% dalam RUPTL itu perlu perubahan radikal untuk mendorong produksi EBT secara signifikan - hal yang sampai saat ini belum terjadi. Sementara target baru seperti pidato Prabowo dianggap mencerminkan ambisi pemerintah yang layak diapresiasi.
Target tak pernah tercapai
Upaya menegaskan dukungan dan arah kebijakan pada EBT sudah dimulai pemerintah sedikitnya sejak satu dekade terakhir. Target transisi dibuat lebih serius dengan memasukkan angka target ke dalam dokumen resmi kebijakan energi nasional tahunan. Dengan masuk kebijakan, maka target tersebut 'mengikat' pelaksana kebijakan agar dicapai dengan berbagai cara.
Kenyataannya, strategi ini tidak berjalan mulus. Sejak awal dicanangkan, target belum pernah tercapai.
Bahkan akhirnya, target untuk 2023 direvisi dari 21% menjadi 17% dalam upaya mengurangi jurang antara target dan realisasi. Koreksi target ini sendiri, dibaca oleh sebagian analis sebagai sikap 'menyerah' pemerintah, posisi yang justru berbalikan dengan semangat untuk 'ngotot' mengejar target.
Berbagai studi menunjukkan ragam alasan kenapa target selalu gagal dicapai.
Alasan utama adalah pendanaan: antara rencana dan realisasi terdapat gap anggaran diperkirakan rata-rata US$7 miliar atau setara dengan Rp113 triliun per tahun.
Pemerintah berupaya menutup kekurangan ini dari berbagai sumber. Namun pengalaman penggalangan dana dari proyek JETP (program Kemitraan untuk Transisi Energi Berkeadilan) misalnya, menunjukkan sebagian besar dana bersifat utang. Selain itu proses pengucuran juga lambat dan penuh birokrasi. Upaya perdana early retirement mempensiunkan PLTU Cirebon-1 misalnya, banyak molor dari jadwal.
Proses penyelesaian transaksi refinancing dan finansial yang tadinya ditargetkan selesai pada Semester I 2024, termasuk komitmen dana dari Asian Development Bank (ADB) dan mitra JETP lainnya, hingga Mei 2025 belum rampung juga.
Begitu pula dengan pembuatan dan finalisasi roadmap transisi yang diharapkan sudah selesai September 2024, tapi malah masih lanjut hingga Maret 2025. Ini salah satu proses kunci karena merinci integrasi pensiun dini dalam RUPTL 2025-2034, di mana pensiun dini PLTU ternyata justru belum masuk perencanaan, walhasil malah memperpanjang ketergantungan pada batubara.
Sebaliknya pada produksi listrik dari batubara, produksi melesat tak terbendung. Menurut data Global Energy Monitor, kapasitas PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia sudah meningkat 6,5 kali lipat selama periode 2000-2024.
Kapasitas terpasang justru mencapai titik tertinggi pada 2024-2025, didorong oleh ekspansi PLTU captive (untuk industri seperti smelter nikel) dan penambahan kapasitas on-grid.
Menurut energyandcleanair.org kapasitas captive naik hampir 10 kali lipat dalam 10 tahun (dari 2,3 GW tahun 2014 ke 15,2 GW di 2024), didorong oleh kebutuhan industri mineral seperti nikel di Sulawesi Tengah (naik dari 2,86 GW ke 5,19 GW pada 2023-2024) dan Maluku Utara.
Sementara lebih dari 12 GW batubara baru beroperasi dalam 5 tahun terakhir, meningkatkan fleet 30%, meski terjadi surplus pasokan di Jawa dan Bali.
Ini menunjukkan bahwa di luar pendanaan, faktor regulasi dan komitmen politik yang tidak konsisten turut menghambat tercapainya target transisi.